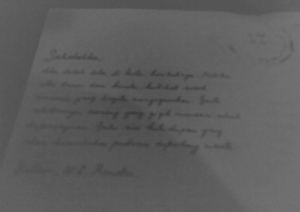Makna Spiritual Dan Sosial Ibadah Puasa
Kolom: Emha Ainun Nadjib

Emha Ainun Nadjib/foto: Nugroho
Tulisan ini bisa dimulai dari perspektif Rukun Islam. Dari syahadah hingga menunaikan haji di rumah suci Allah. Kita mencoba menjelaskan satu per satu maqam Rukun Islam tersebut. Dan, pada akhirnya, kita akan melihat maqam ibadah puasa, yang menjadi topik bahasan tulisan ini. Apakah maqam-maqam itu saling terkait, atau tidak?
‘Alamat’ dan ‘Jurusan’
Syahadah. Salah satu Rukun Islam berarti ketetapan dan penetapan titik pijak dan sekaligus arah tujuan gerak kehidupan manusia Muslim. Semacam ‘alamat’ dan ‘jurusan’. Pertama barangkali pada spektrum kosmologis kemudian teologis, baru kemudian kedua kultural.
Pandangan tentang ‘sangkan paran’, semacam alamat historis-kosmologis, menurut manusia untuk (melalui akal pikiran maupun melalui informasi wahyu, mawaddah wa rahmah, juga huda, bayyinat, wa furqan) menentukan alamat teologis (atau a-teologis)nya. Berdasarkan itu maka ia berangkat merumuskan alamat sosialnya, alamat kulturalnya, juga mungkin alamat politiknya, bahkan bukan tidak mungkin juga alamat geografisnya. Dengan itu, beda pandang manusia mengenai dunia, akhirat, dan tentang dunia akhirat menjadi terumuskan.
Menduniakan Akhirat, Mengakhiratkan Dunia, dan Mendunia-akhiratkan Kehidupan
Pada budaya dan perilaku manusia beserta sistem nilai yang disusun dalam kolektivitas mereka, ada yang memandang dunia ini sebagai tujuan. Seluruh aktivitas pribadi, gerakan sosial, pengorganisasian kekuasaan dan kesejahteraan di antara mereka, dilaksanakan dengan mengandaikan bahwa dunia ini adalah wadah satu-satunya dari segala awal dan segala akhir.
Wadahnya hanya dunia. Substansinya hanya dunia. Metodenya hanya dunia. Dan, targetnya juga hanya dunia. Orang lahir, orang bersekolah, orang bekerja, orang berkuasa, orang berkarier, dalam ‘durasi’ dunia.
Segala sesuatunya akan berbeda dengan pandangan lain yang meletakkan dunia sebagai titik tolak dan titik pijak untuk melangkah ke akhirat. Sejarah di dunia dikerjakan sebagai jalan (syari’, thariq, shirath), dan produknya adalah akhirat. Setiap kegiatan dan fungsi manusia dalam sejarah, selama dunia berlangsung, berlaku sebagai metoda. Berkedudukan tinggi, berjaya, unggul, atau menang di antara manusia, tidak dipahami sebagai neraka. Sebab surga dan neraka adalah produk dari penyikapan (teologis, moral, kultural) manusia atas semua keadaan tersebut.
Dalam hal ini belum akan kita perdebatan tentang apakah dunia dan akhirat itu diwadahi oleh dua satuan waktu yang berbeda, atau terletak pada rentang waktu yang sama, yang dibatasi oleh momentum yawm al-qiyamah, ataukah dunia dan akhirat itu sesungguhnya berlangsung sekaligus.
Ikrar teologis (yang beraktualisasi kultural) yang dilaksanakan melalui syahadatain, ibadah lain serta ‘syariat’ hidup secara menyeluruh adalah suatu pengambilan sikap, suatu pilihan terhadap pandangna atas dunia dan akhirat. Dengan pijakan sikap ini manusia menggerakkan aktivitas sosialnya, melaksanakan upaya-upaya hidupnya, serta menja-dikannya sebagai pedoman di dalam memandang, menghayati dan memperlakukan apapun saja dalam hidupnya.
Tidak termasuk dalam katagori ini pola sikap manusia yang dalam bersyahadat seakan-akan mengambil keputusan teologis yang memetodekan dunia untuk target akhirat, namun dalam praktiknya ia lebih cenderung meletakkan dunia sebagai target dan tujuan.
Kerancuan sikap semacam ini bisa dilatarbelakangi oleh semacam kebutaan (spiritual), oleh inkonsistensi (mental), oleh kemunafikan (moral), atau oleh tiada atau tidak tegaknya pengetahuan (intelektual). Yang terjadi padanya adalah kecenderungan menduniakan akhirat. Sementara pada manusia yang dalam konteks tersebut tercerahkan spiritualitasnya, yang konsisten sikap mentalnya, yang teguh moralnya, dan yang tegak pengetahuannya- kecenderungannya adalah mengakhiratkan dunia, atau dari sisi lain ia bermakna menduniaakhiratkan kehidupan.
Evolusi Salat dan Idul Fitri-Idul Fitri Kecil
Salat. Ibadah Salat merupakan suatu metode ‘rutin’ kultural untuk proses pengakhiratan. Momentum-momentum salat lima waktu memungkinkan manusia pelakunya untuk secara berkala melakukan pengambilan ‘jarak dari dunia’.
Itu bisa berarti suatu disiplin intelektual untuk menjernihkan kembali persepsi-persepsinya, untuk memproporsionalkan dan mensejatikan kembali pandangan-pandangannya terhadap dunia dan isinya, sekaligus itu bermakna ia menemukan kembali kefitrian-diri-kemanusiaan. Salat dengan demikian adalah idul fitri-idul fitri kecil yang bersifat rutin. Sekurang-kurangnya salat mengandung potensi untuk membatalkan atau mengurangi keterjeratan oleh dunia. Ini sama sekali bukan pandangan antidunia. Yang saya maksud, sebagai substansi, target, titik berat atau tujuan kehidupan.
Ibadah salat dengan demikian adalah suatu transisi sistem yang terus-menerus mengingatkan dan mengkodisikan pelakunya yang memelihara sikap mengakhiratkan dunia atau menduniaakhiratkan kehidupan. Ibadah salat menawarkan irama, yaitu proporsi kedunia-akhiratan yang dialektis berlangsung dalam kesadaran, naluri dan perilaku manusia.
Kalau kita idiomatikkan bahwa salat itu bermakna pencahayaan (‘air hujan’, salah satu jenis air yang disebut oleh al-Qur’an), maka jenis ibadah berkala ini berfungsi mencahayai dan mencahayakan kehidupan pelakunya. Mencahayai dalam arti menaburkan alat penjernihan diri dan persepsi hidup. Mencahayakan dalam arti memberi kemungkinan kepada pelakunya untuk bergerak dari konsentrasi kuantitas (benda, materi) menuju dinamika kreativitas (energi) sampai akhirnya menuju atau menjadi kualitas cahaya (Allahu nur al-samawat wa al-ardl).
Ibadah salat bersifat kumulatif dan evolusioner, sebagimana zakat yang berlambangkan susu (jenis air lain yang disebut oleh al-Qur’an). Kambing tidak meminum susunya sendiri, melainkan mendistribusi-kannya kepada anak-anak dan makhluk lain. Etos zakat adalah membersihkan harta perolehan manusia. Membersihkan artinya memproporsikan letak hak dan wajib harta. Manusia tidak memberikan zakat, melainkan membayarkan atau menyampaikan hak orang atau makhluk lain atasnya.
Revolusi Puasa, Melampiaskan dan Mengendalikan
Puasa. Berbeda dengan salat dan zakat, ibadah puasa bersifat lebih ‘revolusioner’ radikal dan frontal. Waktunya pun dilakukan pada masa yang ditentukan, seperti disebutkan al-Qur’an. Dan, waktu puasa wajib sangat terbatas. Hanya pada bulan Ramadhan.
Orang yang berpuasa diperintahkan untuk berhadapan langsung atau meng-engkau-kan wakil-wakil paling wadag dari dunia dan diinstruksikan untuk menolak dan meninggalkannya pada jangka waktu tertentu.
Pada orang salat, dunia dibelakanginya. Pada orang berzakat, dunia di sisinya, namun sebagian ia pilah untuk dibuang. Sementara pada orang berpuasa, dunia ada di hadapannya namun tak boleh dikenyamnya.
Orang berpuasa disuruh langsung berpakaian ketiadaan: tidak makan, tidak minum, dan lain sebagainya. Orang berpuasa diharuskan bersikap ‘tidak’ kepada isi pokok dunia yang berposisi ‘ya’ dalam substansi manusia hidup. Orang berpuasa tidak menggerakkan tangan dan mulut untuk mengambil dan memakan sesuatu yang disenangi; dan itu adalah perang frontal terhadap sesuatu yang sehari-hari meru-pakan tujuan dan kebutuhan.
Puasa adalah pekerjaan menahan di tengah kebiasaan menum-pahkan, atau mengendalikan di tengah tradisi melampiaskan. Pada skala yang besar nanti kita bertemu dengan tesis ini; ekonomi-industri-konsumsi itu mengajak manusia untuk melampiaskan, sementara agama mengajak manusia untuk menahan dan mengendalikan. Keduanya merupakan musuh besar, dan akan berperang frontal jika masing-maisng menjadi lembaga sejarah yang sama kuat.
Sementara ibadah haji adalah puncak ‘pesta pora’ dan demonstrasi dari suatu sikap, pada saat dunia disepelekan dan ditinggalkan. Dunia disadari sebagai sekadar seolah-olah megah.
Ibadah thawaf adalah penemuan perjalanan sejati sesudah seribu jenis perjalanan personal dan personal yang tidak menjanjikan kesejatian dan keabadian. Nanti kita ketahui gerak melingkar thawaf adalah aktualisasi dasar teori inna lillahi wa inna ilayhi raji’un. Suatu perjalanan nonlinier, perjalanan melingkar perjalanan siklikal, perjalanan yang ‘menuju’ dan ‘kembali’nya searah.
Ihram adalah ‘pelecehan’ habis-habisan atas segala pakaian dan hiasan keduniaan yang palsu status sosial, gengsi budaya, pangkat, kepemilikan, kedudukan, kekayaan, atau apapun saja yang sehari-hari diburu oleh manusia. Sehabis berihram mestinya sang pelaku mengerti bahwa nanti kalau ia pulang dan hadir kembali ke kemegahan-kemegahan dunia–tak lagi untuk disembahnya atau dinomorsatukannya. Karena ihramlah puncak mutu dan kekayaan.
Tauhid Vertikal dan Tauhid Horisontal
Adapun apa, ke mana, dan bagaimanakah sesungguhnya yang dijalani oleh para pelaku Rukun Islam, terutama yang ber’revolusi’ dengan puasa?
Pilar utamanya adalah tauhid vertikal (tawhid ilahiyyah) dan tauhid horisontal (tawhid basyariyyah). Tauhid itu proses penyatuan. Penyatuan (ilahiyyah) ke atau dengan Allah, serta penyatuan ke atau dengan sesama manusia atau makhluk, memiliki rumus dan formulanya sendiri-sendiri.
Perlawanan terhadap dunia, penaklukan atas diri dan kehidupan untuk diduniaakhiratkan yang ditawarkan oleh ibadah puasa–sekaligus berarti proses deindividualisasi, bahkan deeksistensialisasi. Tauhid adalah perjalanan deeksistensialisasi, pembebasan dari tidak pentingnya identitas dan rumbai-rumbai sosial keduniaan di hadapan Allah. Segala kedudukan, fungsi dan peran di dunia dipersembahkan atau dilebur ke dalam eksistensi sejati Allah dan kasih sayang-Nya. Tauhid sebagai perjalanan deindividualisasi berarti menyadari dan mengupayakan proses untuk larut menjadi satu atau lenyap ke dalam wujud-qidam-baqa’ Allah. Manusia hanya diadakan, diselenggarakan seolah-olah ada, ada-nya palsu–oleh Yang Sejati Ada.
Yang juga ditawarkan oleh puasa adalah proses dematerialisasi, atau peruhanian atau dalam konteks tertentu pelembutan dan peragian. Dematerialisasi bisa dipahami melalui, umpamanya, konteks peristiwa Isra’ Mi’raj. Rasulullah mengalami proses transformasi dari materi menjadi energi menjadi cahaya. Maka, dematerialisasi vertikal bisa berarti mempersepsikan, menyikapi dan mengolah materi (badan, pemilikan, dunia, perilaku, peristiwa) untuk dienergikan menuju pencapaian cahaya. Fungsi sosial dikerjakan, managemen dijalankan, musik diciptakan, karier ditempuh, ilmu digali dan buku dicetak, uang dicari dan harta dihamparkan–tidak dengan orientasi ke kebuntuan dunia sebagai materi yang fana, melainkan digerakkan ke makna ruhani, pengabdian dan taqarrub kepada Allah, sampai akhirnya masuk dan bergabung ke dalam ‘kosmos’ dan sifat-Nya.
Proses dematerialisasi, proses ruhanisasi atau proses transformasi menuju (bergabung, menjadi) Allah, meminta hal-hal tertentu ditanggalkan dan ditinggalkan. Dalam bahasa sehari-hari orang bilang: jangan mati-matian mencari hal-hal yang tidak bisa dibawa mati.
Menanggalkan dan meninggalkan itu mungkin seperti perjalanan transformasi padi menjadi beras, dan menjadi nasi. Padi menjadi beras dengan menanggalkan kulit. Beras juga padi, tapi beras bukan lagi padi, sebagaimana padi belum beras. Nasi itu substansinya padi atau beras, tapi sudah melalui proses suatu pencapaian transformatif. Para pemakan nasi tidak antipadi, tapi juga tidak makan padi dan menanggalkan kulit padi. Pemakan nasi sangat membutuhkan beras, tapi tidak makan beras dan tidak membiarkan beras tetap jadi gumpalan keras. Pemakan nasi memproses bahan dan substansi yang sama menjadi atau menuju sesuatu yang baru.
Jadi, jika pemburu atau pengabdi Allah tidak antidunia, tidak antimateri, tidak antibenda, tapi juga tidak menyembah benda, melainkan mentransformasikan (mengamalsalehkannya), meruhanikannya (menyaringnya menjadi bermakna akhirat). Bahkan manusia akan menanggalkannya dan meninggalkan dirinya sendiri (gumpalan individu, wajah, badan, performance, eksistensi dunia), karena ‘dirinya’ di akhirat, dirinya yang bergabung ke Allah adalah sosok amal salehnya.
Pada ‘citra’ waktu, dematerialisasi, peruhanian, deindividualisasi, dan deeksistensialisasi berarti pengabdian. Pembebasan dari kesementaraan. Yang ditanggalkan dan ditinggalkan adalah kesementaraan. Segumpal tanah bersifat sementara, tapi ia difungsikan dalam sistem manfaat dan rahmat, maka fungsinya itu mengabdi. Sebagaimana gumpalan badan kita serta segala materi eksistensi kita bersifat sementara, yang menjadi abadi adalah produk ruhani pemfungsian atas semua gumpalan itu.
Melampiaskan dan Mengendalikan
Juga dalam proses tauhid horisontal, penyatuan berarti sosialisasi pribadi. Kalau masih pribadi yang individualistik (ananiyyah), ia gumpalan. Begitu integral-sosial (tawhid basyariyyah), ia mencair, melembut. Yang ananiyyah itu temporer dan berakhir, yang tauhid basyariyah itu baqa’ dan tak berakhir.
Identitas sosial, harta benda, individu, segala jenis pemilikan dunia, dienergikan, diputar, disirkulasikan, didistribusikan, dibersamakan atau diabadikan ke dalam keberbagian sosial. Itulah peruhanian horisontal.
Karena itu, proses-proses menuju keadilan sosial, kemerataan ekonomi, distribusi kesejahteraan, kebersamaan kewenangan dan lain sebagainya–sesungguhnya merupakan aktualisasi tauhid secara horisontal.
Kita tinggal memperhatikan setiap sisi, segmen dan lapisan dari proses sosial umat manusia (pergaulan, kebudayaan, negara, sistem, organisasi) melalui terma-terma materialisasi versus peruhanian, satu versus kemenyatuan, pensementaraan versus pengabdian, penggumpalan versus pelembutan, sampai akhirnya nanti pelampiasan versus pengendalian. Budaya ekonomi-industri-konsumsi kita mengajak manusia untuk melampiaskan. Sementara agama menganjurkan manusia untuk mengendalikan. Kalau kedua arus itu sama-sama menemukan lembaga dan kekuatan sejarahnya yang berimbang, konflik peradaban akan serius.
Ibadah puasa merupakan jalan ‘tol’ bagi perjuangan manusia untuk mencapai kemenangan di tengah tegangan-tegangan konflik tersebut. Juga dalam pergulatan antara iradah al-nas dalam arti individualisme individu-kecil dengan iradah Allah Individu Besar Total.
Kita bisa menolak ke terma sab’a samawat, tujuh langit– Roh-Benda-Tumbuhan-Hewan-Manusia- Ruhanisasi-Ruh– bisa kita temukan siklus-siklus kecil dan besar proses peruhanian yang diselenggarakan oleh manusia.
Atau terma Empat ‘Agama’–‘agama’intuitif-instinktif, ‘agama’ intelektual, ‘agama’ wahyu, serta ‘agama atas agama’--kita bisa menemukan bahwa ketika penerapan wahyu –Agama terjebak menjadi berfungsi gumpalan-gumpalan, maka ‘agama atas agama’ merupakan fenomena peruhanian, kristalisasi substansi. Semua manusia bekerjasama menempuh nilai-nilai inti peruhanian yang mengatasi gumpalan-gumpalan aliran, sekte, kelompok, mazhab atau organisasi agama.
Terma lain yang mungkin bisa kita sentuh adalah cakrawala puasa la’allakum tattaqun. Produk maksimal puasa bagi pelakunya adalah derajat dan kualitas takwa. Dalam terapan empiriknya, kita mencatat stratifikasi fiqh/hukum-akhlak-takwa. Kondisi peradaban umat manusia masih tidak gampang untuk sekadar mencapai tataan manusia fiqh/hukum atau budaya fiqh/hukum. Apalagi naik lebih lagi ke level akhlak dan takwa. []
__________
arsip/1996
![Lola dan calon TKW copyright: @Pic[k]Lock Productions](https://tjontong.files.wordpress.com/2010/06/img_2496.jpg?w=300&h=200)